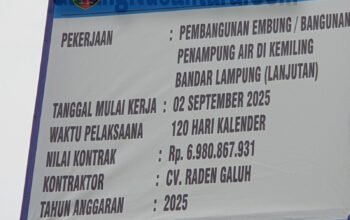Tidak seharusnya hukum pidana digunakan sebagai simbol kekuasaan atau gengsi institusi tertentu, melainkan sebagai alat rasional untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban dan melindungi hak asasi manusia.
1. Asas Ultimum Remedium: Ketika Obat Keras Jadi Santapan Harian
Dalam doktrin hukum pidana modern, pidana adalah obat terakhir — ultimum remedium.
Ia digunakan hanya bila seluruh mekanisme administratif dan keperdataan gagal.
Namun, di tangan penyidik kasus PT LEB, asas itu berubah menjadi sarapan pagi: sesuatu yang dipakai setiap hari, tanpa resep, tanpa diagnosis.
Padahal, dalam kasus PI 10 %, mekanisme non-pidana justru berfungsi sempurna. Ini buktinya:
– Audit KAP berjalan;
– Pengawasan BPKP aktif;
– RUPS diselenggarakan dan menghasilkan keputusan sah;
– Pembayaran dividen telah disetorkan ke pemegang saham.
Tidak ada “kegagalan mekanisme” yang bisa membenarkan masuknya hukum pidana. Yang ada hanyalah keinginan menciptakan drama agar mereka tampak bekerja.
2. Ketika Penyidik Lebih Percaya Dugaan Daripada Data
Penyidik tidak menemukan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya (Pasal 1 angka 22 UU 1/2004).
Namun, mereka tetap berkeras: “kerugian potensial.”
Dalam bahasa medis, ini seperti mengamputasi kaki pasien yang sehat, agar suatu hari kaki tersebut tidak bisa keseleo….
Penegakan hukum seharusnya didasarkan pada kepastian, bukan prasangka. Tapi di sini, prasangka dijadikan alat ukur, dan hukum berubah menjadi horoskop resmi negara.
3. Hukum Pidana Bukan Arena Promosi Pribadi
Setiap konferensi pers, penyidik menampilkan wajah tegang yang lebih mirip juru bicara partai daripada penjaga keadilan. Yang mereka kejar bukan pasal, tapi panggung. Setiap penyitaan menjadi bahan foto; setiap konferensi pers menjadi showcase karier.
Padahal, tugas jaksa bukan menaklukkan media, melainkan meyakinkan akal sehat.
Dan akal sehat tidak bisa dikalahkan oleh volume mikrofon.
4. Rasionalitas Penegakan: Menimbang Sebelum Menuduh
Pasal 8 ayat (1) UU Kejaksaan menegaskan:
> “Penuntutan dilakukan secara independen dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran hukum.”
Independensi di sini berarti bebas dari tekanan, termasuk tekanan internal untuk menonjolkan prestasi.
Namun, dalam kasus PI 10 %, independensi itu runtuh sejak hari pertama.
Penyidikan didorong oleh opini DPRD, desakan publik, dan aroma politik menjelang suksesi daerah.
Hukum dijalankan bukan sebagai sistem, tapi sebagai sensor moral yang ditunggangi kepentingan.
5. Negara Sebagai Korban Hukum Negaranya Sendiri
Kriminalisasi PT LEB menciptakan preseden:
> “Bahwa negara dapat menuduh dirinya sendiri bersalah atas keputusan yang dibuatnya sendiri.”
*Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina Hulu Energi telah mengesahkan seluruh mekanisme PI 10 %. Jika mekanisme itu dianggap melawan hukum, maka seluruh pejabat yang menandatangani persetujuan juga harus ikut terseret.*
Tapi mereka tidak; karena penyidik tidak berani menatap hierarki di atasnya.
Mereka memilih target yang aman: direksi BUMD, pegawai sipil yang tak punya pelindung politik.
Seolah keberanian menurun tajam di hadapan jabatan yang lebih tinggi. Ini bukanlah penegakan hukum — itu penyaluran frustrasi.
6. Pidana Tanpa Kejahatan: Simptom Intelektual
Dalam teori hukum klasik, pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada actus reus (tindakan) dan mens rea (niat jahat). Dalam kasus PT LEB, tidak ada keduanya:
– Semua tindakan dilakukan melalui RUPS yang sah,
– Tidak ada keuntungan pribadi,
– Tidak ada penyembunyian,
– Tidak ada kerugian negara.
Akan tetapi mereka tetap menjerat — mungkin karena tidak tahan pada ruang kosong di tengah sorotan publik. Mereka butuh “penjahat”, meskipun harus menciptakan sendiri.
Hasilnya adalah teater hukum tanpa naskah, di mana aktor tidak mengerti cerita yang ia mainkan.
7. Tafsir Sepihak: Ketika Lex Specialis Dibuang Demi Drama
Permen ESDM 37/2016 dan PP 35/2004 adalah lex specialis. Ia secara eksplisit menegaskan bahwa pengelolaan PI 10 % adalah hak usaha BUMD.
Meskipun demikian, penyidik mengabaikannya dan bersandar pada UU Keuangan Negara, seolah seluruh dunia hanya berisi kas daerah.
Mereka menghapus perbedaan antara “uang hasil usaha” dan “uang pajak.” Kalau logika ini diteruskan, maka setiap BUMN dan BUMD yang memperoleh laba akan otomatis jadi tersangka korupsi. Negara tidak bisa hidup dengan tafsir seperti ini; ia akan lumpuh oleh ketakutan sendiri.
8. Dari Hukum Ke Logika Publik
Rakyat Lampung, yang menyaksikan semua atraksi penyidikan, perlahan mulai paham:
yang dipertontonkan bukan keadilan, tapi ketakutan jaksa akan kehilangan muka.
Dan di situlah hukum kehilangan wibawanya:
ketika publik mulai menganggap penyidik sebagai pemain sinetron, bukan sebagai pemegang kebenaran.
Ending yang Hampa
1. Asas ultimum remedium dilanggar; hukum pidana dipakai sebelum seluruh mekanisme administratif diuji.
2. Tidak ada kerugian negara yang nyata; penuntutan didasarkan pada asumsi politis.
3. Kriminalisasi PT LEB berarti kriminalisasi sistem nasional PI 10 % yang disahkan oleh ESDM dan SKK Migas.
4. Jaksa telah menjadikan publikasi sebagai alat legitimasi, bukan pembuktian.
5. Hukum yang seharusnya menjadi penuntun nalar berubah menjadi pertunjukan ambisi.
> “Keadilan tidak membutuhkan sorotan kamera.
Ia cukup berjalan pelan, beralas nalar, dan tidak takut kehilangan panggung.”