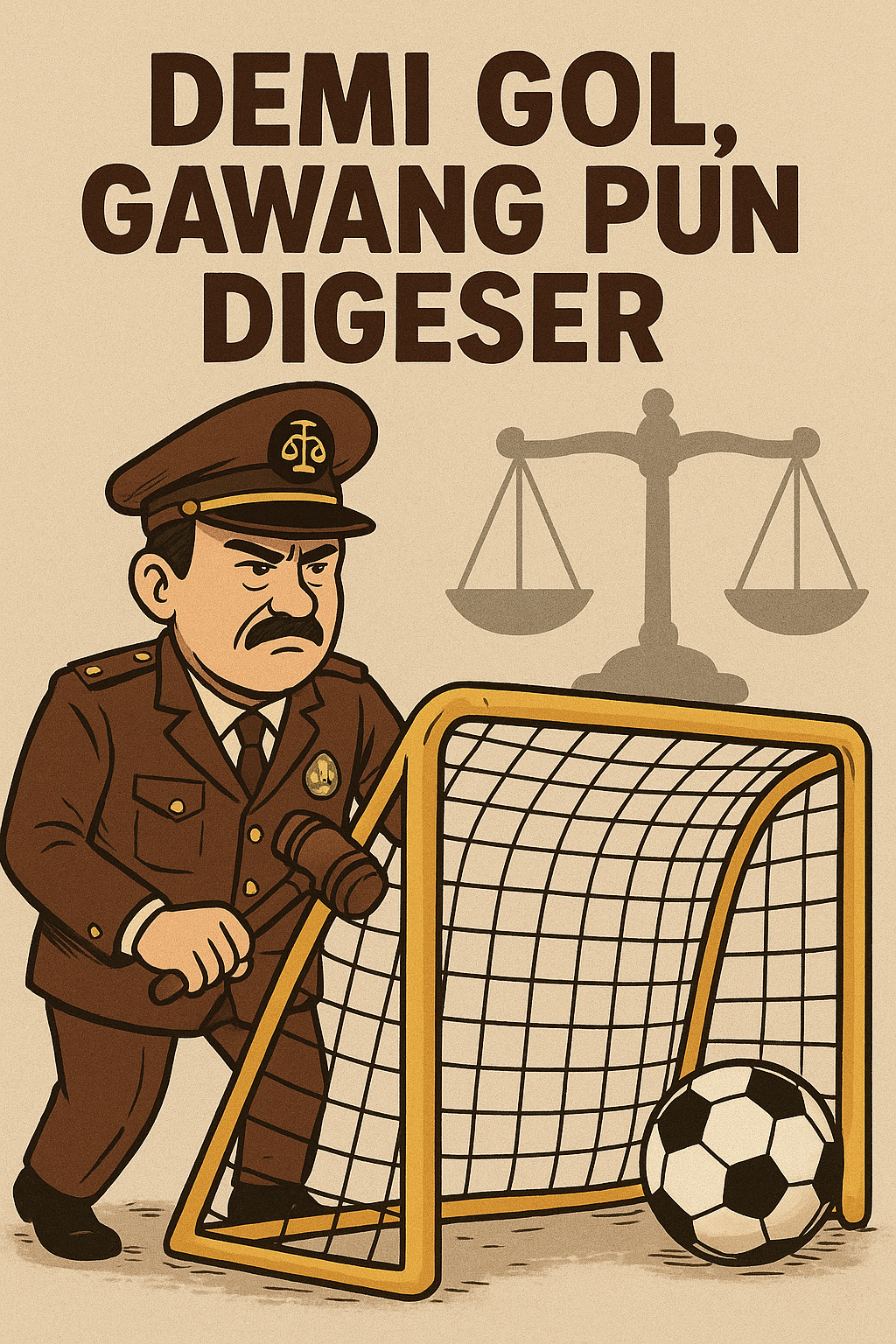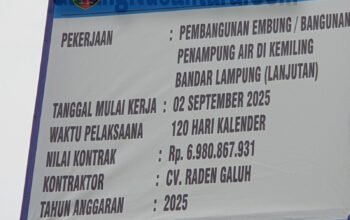GalangNusantara.com
Ketika Jaksa Berpikir Hukum Itu Panggung, dan Bukti Cukup Diganti Narasi
1. Ketika Narasi Menang atas Bukti
Satu tahun lebih mereka berputar, puluhan saksi diperiksa, rumah gubernur, kantornl LEB, LJU, dan kantor dan rumah direktur PDAM Way Guruh Lampung Timur, rumah direksi, dan komisaris digeledah, tumpukan uang dijejer di meja konferensi pers.
Tapi apa yang ditemukan? Tidak ada angka resmi kerugian negara. Tidak ada audit BPKP. Tidak ada laporan keuangan yang menandakan penyimpangan.
Namun mereka tetap maju—karena bukan bukti yang mereka kejar, melainkan tepuk tangan publik. Mereka tahu, dalam opini publik yang lapar sensasi, logika hukum kalah oleh visualisasi kamera.
Maka jadilah drama: gebrakan penyitaan, foto-foto dolar, pengumuman “akan ada tersangka baru,” dan istilah klasik yang sering muncul di konferensi pers mereka:
> “Masih terus kami dalami.”
Padahal yang terus mereka dalami bukan perkara, tetapi cara bertahan hidup dari janji mereka sendiri kepada publik.
2. “Atraksi” yang Menggantikan Pembuktian
Satu tahun penyidikan seharusnya cukup untuk menuntaskan perkara apa pun. Tapi dalam kasus PI 10%, semakin lama berjalan, semakin terlihat bahwa Kejati Lampung tak punya arah.
Seperti kapal tanpa kompas, mereka terus berlayar hanya karena takut diakui tersesat.
Alih-alih mengakui ketiadaan unsur pidana, mereka menciptakan istilah baru:
> “Potensi kerugian negara.”
Sebuah konsep yang tak dikenal dalam hukum positif Indonesia, tetapi sering dipakai bila bukti tidak cukup, tapi gengsi terlalu besar untuk mundur.
Mereka memaksa setiap transaksi korporasi seolah dana publik,
setiap keputusan direksi seolah kejahatan,
setiap laporan keuangan seolah rekayasa.
Padahal semua telah melalui RUPS, audit, dan pengawasan berlapis.
Hasilnya: bukan penegakan hukum, tapi eksperimen kebodohan birokrasi dalam bentuk paling telanjang.
3. Kesalahan Fatal: Menganggap Dividen sebagai Dana Publik
Logika penyidik sederhana tapi salah besar:
> “Karena PT LEB adalah BUMD, maka seluruh uangnya adalah uang negara.”
Padahal PP 54 Tahun 2017 telah membatasi dengan jelas bahwa yang menjadi Pendapatan Daerah hanyalah dividen yang diputuskan RUPS.
Selebihnya adalah urusan korporasi.
Mereka seperti jaksa yang tidak pernah membaca PP yang mereka kutip. Mereka memukul rata seluruh laba korporasi sebagai “uang negara,”
sama seperti orang yang menyebut seluruh uang di dompet bankir sebagai “uang bank.”
4. Ketika Jaksa Menolak Logika, Tapi Meminta Percaya
BPKP sudah menolak menghitung kerugian. BPK juga mengatakan tidak ada indikasi fraud.
Audit independen menyatakan laporan keuangan bersih dan LEB mendapat opini WTP.
Dividen Rp 214 miliar disetor penuh, pajak dibayar, laporan diaudit, dan seluruh saldo kas tercatat.
Namun jaksa tetap berkeras:
> “Ada kerugian negara, tapi belum bisa disebut angkanya.”
Mereka ingin publik percaya pada sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak pahami.
Hukum berubah menjadi iman buta terhadap tuduhan. Dan dalam kebutaan itu, yang mereka kejar bukan keadilan, melainkan pangkat dan promosi.
5. Dari Penyelidikan ke Panggung Karier
Publik tak bodoh. Mereka tahu, setiap “kasus besar” yang gagal berakhir di pengadilan tetapi gemerlap di media, biasanya hanya memiliki satu makna: ada seseorang yang sedang membangun tangga karier.
Kasus PI 10% Lampung tidak lain adalah panggung gladi resik bagi ambisi pribadi:
menjadi pahlawan fiktif dalam drama yang diciptakan sendiri.
Tapi bedanya, kali ini publik memiliki data.
Dan data tidak bisa dikalahkan dengan narasi.
6. Keputusan Menggeser Gawang
1. Penyidikan ini kehilangan arah hukum dan bergeser menjadi atraksi publik. Agar gol, letak gawang pun digeser.
2. Jaksa bertindak tanpa dasar bukti audit, mengandalkan dugaan untuk menggantikan perhitungan.
3. Kejati Lampung gagal membedakan uang korporasi dengan uang negara.
4. Proses hukum berubah menjadi proyek pencitraan, bukan pembuktian.
5. Dalam sejarah penegakan hukum modern, tidak ada yang lebih memalukan daripada jaksa yang kalah oleh bukti lalu menyalahkan laporan keuangan.